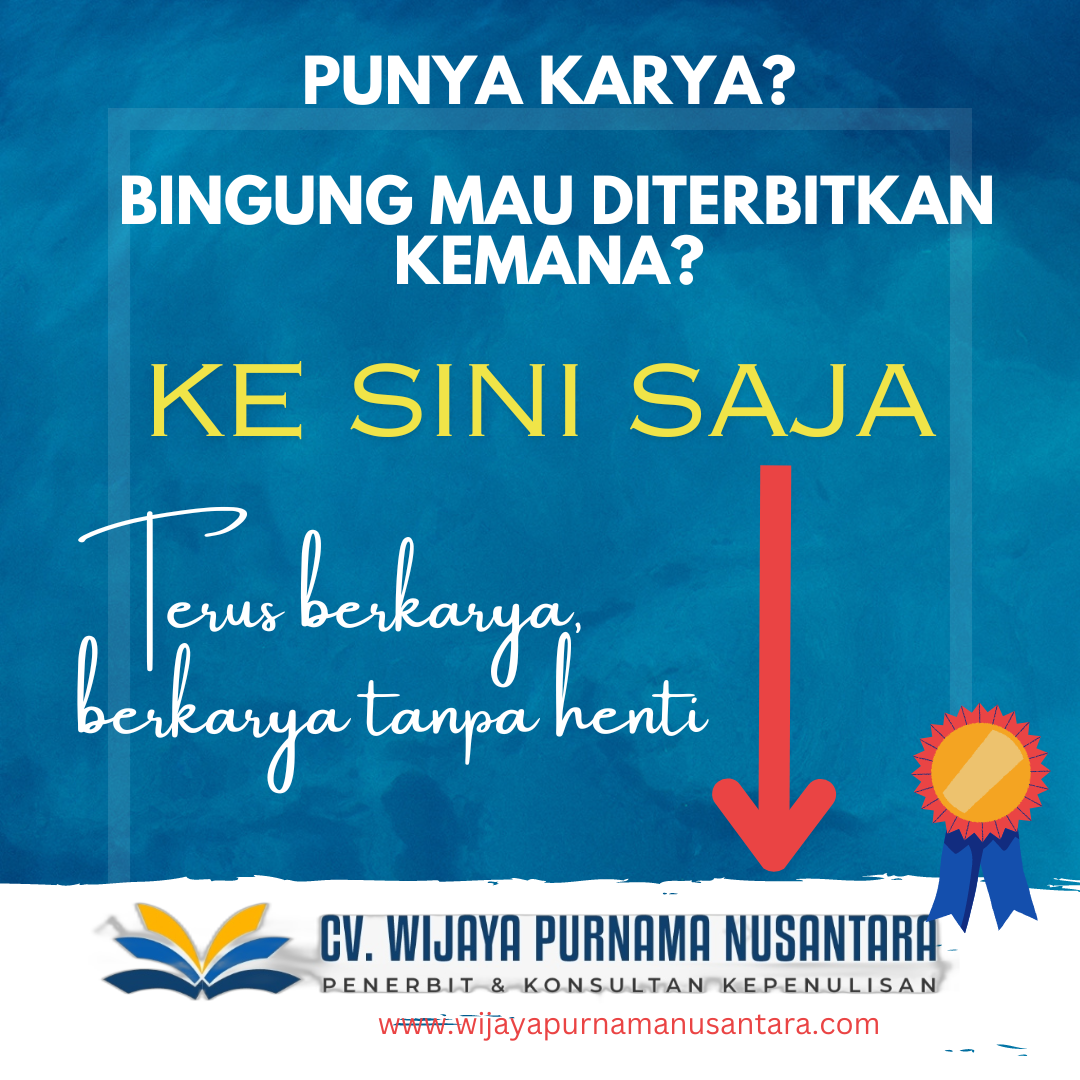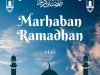KABAR-DESAKU.COM – Delapan puluh tujuh tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai penjuru nusantara mengikrarkan janji suci kebangsaan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda.
Sebuah ikrar monumental yang meneguhkan cita-cita besar: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa—Indonesia.
Tiga kalimat sederhana itu bukan sekadar retorika, melainkan kontrak sosial dan moral yang menjadi fondasi berdirinya bangsa ini.
Dari semangat persatuan itulah lahir keberanian kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan, menepis sekat-sekat kedaerahan, dan menumbuhkan kesadaran nasional.
Namun kini, di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, pertanyaan yang muncul adalah: masihkah semangat “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” relevan di era modern ini?
Baca juga: Rumah Baca Purnama Gelar Pelatihan Read Aloud, Ternyata Ini Manfaat Dahsyatnya
Nasionalisme di Tengah Arus Global
Era digital menghadirkan paradoks baru. Di satu sisi, teknologi informasi mempercepat komunikasi dan memperluas wawasan.
Dunia terasa tanpa batas. Tetapi di sisi lain, globalisasi digital juga membawa ancaman terhadap identitas nasional.
Fenomena disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi daring, serta lunturnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik menjadi gejala nyata.
Sementara itu, generasi muda lebih akrab dengan bahasa gaul global atau istilah asing yang kadang mengaburkan jati diri kebahasaannya.
Di sinilah relevansi Sumpah Pemuda diuji. “Satu nusa” bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga kesadaran menjaga ruang digital sebagai bagian dari tanah air. “Satu bangsa” berarti merawat persaudaraan di tengah keragaman opini dan pilihan. Dan “satu bahasa” bukan sekadar alat komunikasi, melainkan penanda identitas kultural bangsa Indonesia.
Bahasa Indonesia di Era Digital
Bahasa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pemersatu bangsa. Di tengah pluralitas etnis dan budaya, bahasa nasional menjadi simbol kesetaraan.
Namun di ruang digital, kita mulai melihat degradasi sikap berbahasa: maraknya ujaran kasar, konten provokatif, serta campur-aduk bahasa yang mengaburkan makna komunikasi publik.
Bahasa seharusnya tidak hanya dimengerti, tetapi juga menyatukan. Maka, menjadi tugas kita bersama — terutama insan pendidikan — untuk menjaga marwah bahasa Indonesia di dunia digital.
Sekolah perlu menanamkan literasi digital yang beretika, agar siswa tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga berkarakter dalam berkomunikasi.
Dalam konteks pendidikan, guru bahasa, PAI, dan kewarganegaraan perlu bersinergi menanamkan nilai-nilai nasionalisme digital: berpikir kritis, santun dalam berpendapat, dan bangga menggunakan bahasa Indonesia di ruang maya.
Baca juga: Potensi Batik Purbalingga dalam Dinamika Peradaban Modern
Pendidikan dan Spirit Kebangsaan
Sumpah Pemuda bukan sekadar sejarah untuk dihafal setiap Oktober, melainkan nilai yang harus dihidupi. Di sekolah-sekolah, terutama tingkat SMP, pendidikan karakter kebangsaan harus mendapat ruang yang kreatif dan kontekstual.
Kegiatan seperti lomba kebahasaan, literasi digital, atau proyek kolaboratif antar-siswa dari berbagai daerah dapat menjadi wahana menumbuhkan semangat kebangsaan di era teknologi.
Sebagai pengurus MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), kami melihat pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan rasa bangga menjadi pelajar Indonesia.
Guru bukan hanya pengajar mata pelajaran, tetapi penyemai nilai-nilai kebangsaan. Sementara siswa, sebagai generasi digital, harus diajak untuk memahami bahwa mencintai Indonesia tidak lagi cukup dengan lagu kebangsaan, tetapi juga dengan cara berperilaku etis dan bertanggung jawab di dunia maya.
Digitalisasi dengan Jiwa Nasionalis
Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Ia akan bernilai ketika digunakan untuk memperkuat kemanusiaan dan kebangsaan.
Semangat “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” harus menjadi kompas moral dalam penggunaan teknologi digital.
Sebagai bangsa besar, kita tidak boleh kehilangan akar budaya dan jati diri. Di tengah derasnya informasi global, identitas Indonesia harus menjadi filter, bukan korban.
Pemuda masa kini perlu memaknai nasionalisme bukan dalam bentuk slogan, melainkan dalam tindakan: mencintai produk lokal, melestarikan budaya, menjaga sopan santun digital, dan berpartisipasi aktif membangun masyarakat yang damai dan inklusif.
Meneguhkan Kembali Semangat Persatuan
Sumpah Pemuda adalah warisan luhur, tetapi juga tantangan zaman. Tugas generasi hari ini adalah menyambung semangat itu ke masa depan.
Kita harus mampu menjadikan teknologi sebagai jembatan persaudaraan, bukan tembok perpecahan; menjadikan bahasa Indonesia sebagai perekat identitas, bukan sekadar alat percakapan; dan menjadikan semangat persatuan sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi kompleksitas era digital.
Ketika generasi muda Indonesia mampu menghidupkan kembali semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dalam kehidupan digitalnya, maka cita-cita para pemuda 1928 tidak akan redup—ia justru menemukan bentuk barunya yang relevan, cerdas, dan berkarakter.***
Ditulus oleh: Priyanto (Pengurus MKKS SMP Kabupaten Purbalingga)